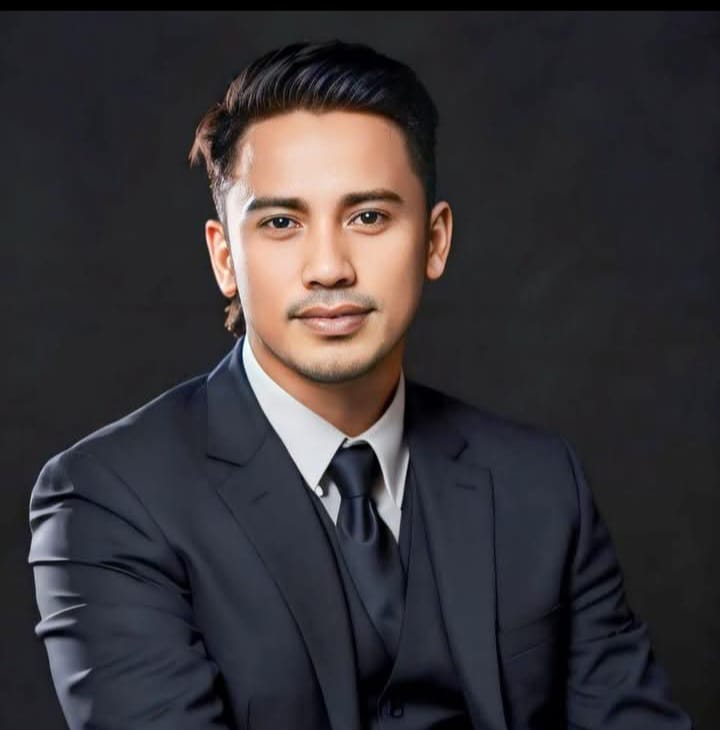Oleh: Nev Setiawan
Di tengah gegap gempita pembangunan desa dan semangat nasionalisme yang ditegaskan dengan warna merah putih, pemerintah meluncurkan satu program ambisius: Koperasi Merah Putih. Dengan target membangun 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan Indonesia, gagasan ini tidak hanya menandai lompatan administratif, tetapi juga menawarkan harapan baru atas wajah ekonomi rakyat yang lebih mandiri dan berdaulat. Namun, seperti sejarah yang sering berulang dalam wajah berbeda, muncul pertanyaan mendasar: apakah ini tidak terlalu buru-buru?
Antusiasme yang Mungkin Terlalu Cepat
Dibayangi oleh agenda besar pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan penguatan UMKM, program Koperasi Merah Putih tampak menjanjikan di atas kertas. Pemerintah menawarkan skema yang ambisius: pembiayaan koperasi desa hingga Rp5 miliar, unit usaha lengkap mulai dari simpan pinjam, pengolahan hasil tani, logistik, hingga layanan kesehatan. Pendampingan teknis dikabarkan tersedia. Skema bisnis sudah digambar. Target nasional sudah ditetapkan.
Namun dalam geliat program yang massif, ada keraguan yang mengendap: apakah masyarakat desa sungguh dilibatkan sejak awal? Apakah koperasi ini lahir dari kebutuhan kolektif, atau sekadar datang dari pusat sebagai proyek siap edar yang harus dijalankan demi memenuhi target angka?
Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan daftar fasilitas atau nominal anggaran. Sebab koperasi bukan soal bangunan, bukan pula hanya tentang modal usaha. Koperasi adalah organisme sosial, tempat pendidikan kesadaran ekonomi, ruang belajar demokrasi, dan alat perjuangan bersama. Ia hidup bukan karena dana, melainkan karena partisipasi sadar para anggotanya.
Lebih jauh lagi, muncul satu persoalan mendesak yang kerap luput dari perhatian dalam peluncuran program besar semacam ini: siapa yang akan mengelola koperasi-koperasi ini?
Di banyak desa, kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola koperasi belum terbangun secara memadai. Banyak pengurus koperasi terdorong maju bukan karena kompetensi, tetapi karena kedekatan dengan pemerintah desa atau sekadar karena “tidak ada orang lain”. Tak sedikit pula yang menganggap koperasi hanyalah “perpanjangan tangan program bantuan”, bukan badan usaha berbasis anggota.
Tanpa pelatihan intensif dan berkelanjutan, koperasi yang didirikan secara top-down berisiko besar menjadi wadah kosong. Ia mungkin aktif secara administratif — rapat ada, proposal jalan, laporan dibuat — tetapi kosong secara substansi partisipasi dan semangat kolektif.
Lebih gawat lagi, tanpa manajemen yang profesional dan akuntabel, koperasi bisa mudah tergelincir menjadi alat segelintir elite desa. Potensi penyalahgunaan dana, korupsi internal, dan konflik antaranggota akan semakin besar bila tidak ada sistem pengawasan partisipatif dan mekanisme kontrol sosial dari anggota sendiri.
Inilah mengapa, koperasi tidak bisa dilahirkan secara instan. Ia harus dididik, dijemput dengan kesabaran. Dibutuhkan waktu untuk membangun pemahaman dasar tentang koperasi — apa itu anggota, apa itu modal sosial, bagaimana membangun kepercayaan, bagaimana mengambil keputusan bersama, dan bagaimana bertanggung jawab terhadap dana kolektif.
Jika ini diabaikan, maka koperasi hanya akan menjadi proyek infrastruktur sosial yang kosong makna. Gedung ada, papan nama dipasang, buku simpan pinjam disusun — tapi kehidupan koperasinya tidak berjalan. Ia menjadi koperasi administratif, bukan koperasi gerakan.
Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah — baik pusat maupun daerah — untuk mengalihkan fokus dari sekadar “banyaknya koperasi berdiri” ke soal “bagaimana kualitas kesiapannya”. Program pelatihan pengelola koperasi harus menjadi fondasi utama. Bahkan sebelum koperasi didirikan, warga desa harus melalui tahap pemahaman bersama tentang tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
Sebab koperasi, pada dasarnya, adalah pendidikan terus-menerus tentang tanggung jawab bersama. Ia tak bisa dilahirkan lewat instruksi atau anggaran. Seperti pepatah lama yang kembali relevan hari ini:
“Koperasi itu mendidik, bukan mendadak.”
KUD: Bayangan yang Masih Menghantui
Tak bisa dipungkiri, program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan hari ini memantik memori kolektif tentang Koperasi Unit Desa (KUD) — entitas ekonomi desa yang pernah begitu dominan pada masa Orde Baru. Didirikan dengan semangat seragam dan dorongan penuh dari negara, KUD kala itu menjadi “perpanjangan tangan” kebijakan ekonomi nasional di tingkat akar rumput. Ia bertugas sebagai agen distribusi pupuk, perantara hasil panen, penyedia kredit, hingga penyalur berbagai jenis bantuan pemerintah. Dalam konstruksi pembangunan yang sentralistik, KUD didapuk sebagai tulang punggung ekonomi desa.
Namun, seiring waktu, KUD tak mampu bertahan sebagai institusi ekonomi yang hidup dan relevan. Banyak yang kemudian kolaps, stagnan, atau berubah menjadi lembaga mati suri yang hanya hidup di papan nama dan laporan tahunan. Pertanyaannya: apa yang membuat KUD gagal? Dan yang lebih penting: bagaimana agar Koperasi Merah Putih tidak terjerumus ke dalam lubang sejarah yang sama?
1. Lahir Bukan dari Inisiatif Anggota, Melainkan Instruksi Atasan
Salah satu akar kegagalan KUD adalah tidak adanya kepemilikan sosial dari masyarakat desa. KUD bukanlah koperasi yang tumbuh dari kesadaran kolektif atau kebutuhan nyata warga. Ia dibentuk lewat perintah struktural, dengan desain yang nyaris seragam dari Sabang sampai Merauke. Tak ada ruang bagi keragaman sosial-ekonomi desa. Tak ada waktu untuk membangun pemahaman warga.
Akibatnya, KUD hanya menjadi alat pelaksana program, bukan komunitas ekonomi. Anggota tidak merasa memiliki. Partisipasi menjadi formalitas. Rapat anggota sekadar prosedur. Semua kegiatan dikendalikan oleh pengurus yang sering kali ditunjuk, bukan dipilih secara demokratis.
Jika Koperasi Merah Putih lahir dengan skema yang mirip — turun dari atas, dibentuk cepat demi target angka, dan tidak memberi ruang partisipasi sejak awal — maka risiko kegagalan struktural akan kembali mengintai.
2. Terlalu Bergantung pada Negara
KUD juga tumbuh dalam ekosistem ketergantungan kronis terhadap negara. Ia diberi subsidi, difasilitasi infrastruktur, dilimpahi kewenangan distribusi, tetapi tidak pernah diajarkan cara bertahan di pasar bebas. Ketika subsidi ditarik dan liberalisasi ekonomi diberlakukan di era 1990-an, banyak KUD limbung. Mereka tidak siap bersaing secara mandiri, karena selama ini tidak dibentuk sebagai pelaku usaha yang tangguh, melainkan sebagai operator proyek pemerintah.
Jika Koperasi Merah Putih kembali dimanjakan dengan fasilitas besar tanpa pendidikan kemandirian dan kemampuan manajerial, maka situasinya hanya akan menjadi pengulangan. Bantuan Rp5 miliar, gudang, dan klinik desa bisa jadi tidak lebih dari bangunan kosong, jika tidak disertai dengan kemampuan bertahan hidup di luar dana negara.
3. Politik Lokal dan Korupsi Struktural
KUD juga rawan dijadikan alat kekuasaan lokal. Pemilihan pengurus kerap didominasi elite desa atau birokrat. Transparansi keuangan minim. Pengurus merasa lebih bertanggung jawab pada “atasan” di dinas koperasi daripada kepada anggota. Situasi ini membuka jalan bagi praktik-praktik korupsi struktural — penggelapan dana, mark-up aset, atau sekadar ketidakjujuran dalam pembagian keuntungan.
Inilah mengapa, ketika kontrol sosial dari anggota lemah, koperasi bisa menjadi wadah yang disalahgunakan, bukan untuk pemberdayaan, tapi justru untuk memperkuat ketimpangan kekuasaan di tingkat lokal.
Koperasi Merah Putih harus belajar dari luka ini. Jangan sampai pengelolaan dana koperasi desa hanya jadi bancakan elite lokal yang berkolusi dengan proyek-proyek pemerintah. Perlu sistem demokrasi internal koperasi yang ketat, keterbukaan informasi, dan pelibatan aktif anggota dalam pengambilan keputusan.
4. Struktur yang Terlalu Baku dan Tidak Kontekstual
Salah satu kelemahan desain KUD adalah struktur kelembagaan yang terlalu seragam dan tidak adaptif terhadap kondisi lokal. Semua desa dianggap memiliki masalah dan kebutuhan yang sama. Padahal, karakter desa nelayan tentu berbeda dengan desa pertanian dataran tinggi. KUD tidak punya fleksibilitas untuk menyesuaikan diri, karena sistemnya dikendalikan dari atas.
Jika Koperasi Merah Putih mengulang pola ini — satu model diterapkan seragam di seluruh desa, tanpa menghitung keragaman sosial, budaya, dan sumber daya — maka kegagalannya sudah bisa diprediksi.
Membangun koperasi desa adalah langkah strategis yang bisa memberi harapan baru bagi kedaulatan ekonomi rakyat. Namun antusiasme saja tidak cukup. Butuh kehati-hatian, kesabaran, dan pelajaran dari sejarah.
Jangan biarkan Koperasi Merah Putih menjadi “KUD jilid dua” — penuh niat baik, tetapi buruk dalam implementasi. Jangan sampai kegagalan yang telah kita pahami, justru kita ulangi hanya karena tergesa dan lapar prestasi.
Sebab koperasi sejatinya bukan tentang membangun struktur, tetapi menumbuhkan kultur. Dan seperti kata bijak yang kini menjadi pengingat keras bagi kita semua:
koperasi itu mendidik, bukan mendadak.
BUMDes: Di Mana Posisi Mereka?
Masalah lain yang tak kalah penting dalam euforia pembentukan Koperasi Merah Putih adalah nasib dan posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejak dilegalkan lewat Undang-Undang Desa tahun 2014, BUMDes telah menjadi simbol kemandirian ekonomi desa. Mereka dibentuk oleh desa, dikelola bersama oleh perangkat dan masyarakat, dengan mandat yang kuat: memanfaatkan potensi lokal secara kolektif demi kesejahteraan warga.
Dalam satu dekade terakhir, BUMDes telah tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang relatif mapan — meski tentu masih menghadapi banyak tantangan. Dari unit usaha air bersih, persewaan alat pertanian, simpan pinjam, toko sembako, hingga pengelolaan pasar desa, BUMDes mencoba menjadi garda depan dalam membangkitkan ekonomi lokal berbasis aset desa.
Namun kini, hadirnya Koperasi Merah Putih memunculkan pertanyaan strategis yang belum dijawab secara terbuka: di mana posisi BUMDes dalam skema pembangunan ekonomi desa ke depan? Apakah ia akan tetap jadi aktor utama, atau justru pelan-pelan dikesampingkan oleh entitas baru yang didorong kuat dari pusat?
Lebih jauh, muncul potensi tumpang tindih kelembagaan. Bayangkan satu desa kecil — dengan sumber daya manusia terbatas — kini harus mengelola dua lembaga ekonomi sekaligus: BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Keduanya berambisi membuka unit usaha simpan pinjam, toko sembako, dan pengelolaan hasil pertanian. Apakah mereka bersaing, atau bersinergi?
Di atas kertas, tentu sinergi adalah kata kunci. Dalam desain ideal, BUMDes dan koperasi bisa saling melengkapi:
* BUMDes bisa fokus membangun infrastruktur dasar: gudang komunal, alat transportasi, pasar desa, dan akses ke digitalisasi layanan.
* Koperasi bisa memfokuskan diri pada penguatan basis anggotanya: meningkatkan literasi keuangan warga, mengelola unit usaha kolektif, dan menjadikan desa sebagai komunitas ekonomi berbasis demokrasi partisipatif.
Namun dalam praktiknya, sinergi tidak mungkin terjadi tanpa desain kelembagaan yang jelas dan peta jalan yang terarah. Jika pembagian peran tidak diatur secara tegas, kompetisi tak sehat bisa terjadi. Terutama jika kedua lembaga ini menjadi kendaraan politik yang berbeda: satu dikelola oleh kepala desa dan perangkatnya, satu lagi oleh kelompok masyarakat atau elite lain yang punya relasi ke kementerian atau lembaga pendamping koperasi.
Apalagi, struktur sosial desa tidak pernah steril dari tarik-menarik kekuasaan. Dalam banyak kasus, BUMDes pun sudah mulai terdorong menjauh dari mandat kolektifnya karena terlalu dekat dengan kekuasaan lokal — menjelma menjadi “BUMDes kepala desa”, bukan BUMDes warga. Jika Koperasi Merah Putih tidak punya mekanisme partisipatif yang kuat, ia bisa jatuh ke lubang yang sama: jadi alat baru bagi kekuasaan lokal, bukan sarana emansipasi warga.
Ketiadaan koordinasi antar lembaga desa juga bisa memunculkan beban administratif tambahan: laporan dobel, konflik keuangan, tumpang tindih perizinan, hingga perebutan aset desa yang dikelola dua lembaga berbeda.
Pemerintah pusat dan daerah harus segera menjawab dilema ini, bukan menundanya hingga konflik terjadi di lapangan. Diperlukan:
* Kebijakan integratif yang mengatur hubungan kelembagaan antara BUMDes dan koperasi di tingkat desa.
* Panduan teknis yang menjelaskan pembagian peran dan model sinergi yang bisa diterapkan sesuai konteks sosial desa.
* Fasilitasi forum musyawarah desa sebagai ruang perundingan antara pengurus BUMDes, koperasi, perangkat desa, dan warga — agar tidak terjadi dominasi satu lembaga atas yang lain.
Tanpa langkah-langkah ini, BUMDes dan Koperasi Merah Putih justru bisa saling menggerus, bukannya saling menopang. Bukan tidak mungkin, dua lembaga yang sama-sama punya cita-cita mulia itu justru menjadi kompetitor yang saling menjatuhkan, mengulangi pola konflik antar institusi desa yang dulu pernah terjadi saat program-program pemerintah datang tanpa peta sosial yang memadai.
Jika itu yang terjadi, maka yang rugi bukan hanya lembaga, tetapi warga desa itu sendiri — yang seharusnya menjadi pemilik sah dari seluruh proses pembangunan ekonomi di desanya.
Saran: Menyemai, Bukan Menanam Paksa
Jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat, maka ia harus meninggalkan cara berpikir proyek yang instan dan seragam. Koperasi bukanlah produk, melainkan proses. Ia tidak bisa dipaksakan tumbuh dari atas, apalagi dalam tenggat waktu yang dibatasi logika anggaran. Sebaliknya, koperasi harus disemai dari bawah — dari tanah sosial yang hidup, dari kebutuhan yang nyata, dan dari relasi kepercayaan yang tumbuh di antara warga desa.
Budaya berkoperasi bukanlah hasil dari sosialisasi seminggu atau pelatihan tiga hari, melainkan hasil dari pendidikan panjang, pembiasaan, dan percontohan konkret yang menunjukkan manfaat bersama. Kita perlu mengingat kembali bahwa koperasi sejatinya adalah gerakan, bukan lembaga teknokratis belaka. Ia harus membentuk karakter kolektif, bukan sekadar struktur bisnis baru.
Berikut beberapa saran strategis yang dapat menjadi arah koreksi atas pendekatan yang terlalu tergesa:
1. Berikan Waktu dan Ruang untuk Pertumbuhan Alami
Tidak semua desa punya kesiapan sosial, kapasitas SDM, atau kebutuhan yang sama. Maka, hindari pendekatan seragam dalam pembentukan koperasi. Biarkan tiap desa menentukan waktu yang tepat, bentuk koperasi yang relevan, dan bidang usaha yang sesuai dengan potensi lokalnya. Pemerintah cukup memberikan dukungan fasilitatif, bukan paksaan administratif.
2. Dorong Integrasi Strategis dengan BUMDes
Jangan tempatkan koperasi sebagai pesaing BUMDes. Keduanya bisa menjadi dua kaki ekonomi desa yang berjalan berdampingan. Pemerintah perlu segera merumuskan skema regulasi yang menjelaskan batas peran, potensi kolaborasi, dan mekanisme sinergi antara keduanya. Misalnya, koperasi dapat memanfaatkan fasilitas BUMDes sebagai mitra distribusi, sedangkan BUMDes dapat mempercayakan pengelolaan unit usaha mikro ke koperasi.
3. Fokus pada Penguatan SDM Koperasi
Koperasi tidak akan sehat tanpa pengelola yang berintegritas dan cakap. Maka, pendidikan menjadi kunci utama. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pelatihan manajemen koperasi, akuntansi partisipatif, kepemimpinan kolektif, dan mediasi konflik. Jangan biarkan koperasi hanya dikelola oleh “orang dekat” atau “pengurus titipan” yang tak paham prinsip koperasi. Koperasi itu mendidik, bukan mendadak — dan itu berlaku juga bagi pengurusnya.
4. Lindungi Koperasi dari Politisasi
Terlalu banyak koperasi yang mati muda karena dijadikan alat kampanye atau ditumpangi kepentingan elite lokal. Jika Koperasi Merah Putih hanya jadi etalase program atau pelengkap narasi politik pembangunan, maka nasibnya bisa lebih buruk dari KUD. Pemerintah perlu membuat mekanisme pengawasan independen dan mendorong keterlibatan warga secara aktif dan kritis, agar koperasi benar-benar milik bersama, bukan milik segelintir orang.
5. Hidupkan Semangat Gerakan, Bukan Sekadar Administrasi
Sudah saatnya koperasi dikembalikan pada roh awalnya sebagai gerakan rakyat. Bukan hanya laporan tahunan, bukan hanya rapat pengurus, tapi sebagai ruang belajar bersama tentang solidaritas ekonomi, demokrasi sehari-hari, dan keberdayaan kolektif. Koperasi harus menjadi tempat di mana warga belajar memutuskan bersama, mengambil tanggung jawab bersama, dan berbagi hasil bersama.
Penutup
Koperasi Merah Putih menyimpan harapan besar bagi masa depan ekonomi desa — tetapi harapan itu tidak bisa digantungkan hanya pada modal besar dan instruksi pusat. Ia harus bertumbuh dalam kesabaran, dalam partisipasi warga, dan dalam proses pendidikan sosial yang berkelanjutan.
Mendirikan koperasi itu mudah. Tetapi membangun kesadaran berkoperasi adalah kerja lintas generasi. Dibutuhkan waktu, ketekunan, dan komitmen pada nilai-nilai gotong royong.
Seperti tanaman yang baik, koperasi hanya bisa tumbuh jika ditanam pada tanah sosial yang subur, disiram oleh partisipasi yang tulus, dan disinari oleh pendidikan yang membebaskan. Sebab sekali lagi:
koperasi itu mendidik, bukan mendadak.